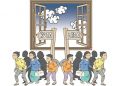oleh: Ace Hasan Syadzily ( Gubernur Lemhannas RI)
Lanskap seperti ini tak bisa dikesampingkan karena terkait daya tahan warga negara kita. Ketahanan individu bangsa kita harus teruji di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini.
Ada satu dimensi yang sering luput, padahal itu menjadi penentu bagi sebuah bangsa agar terus tegak berdiri, atau justru runtuh dari dalam, yaitu kesehatan mental warga negaranya.
Ketahanan nasional yang kokoh harus berakar pada ketahanan pribadi. Di sini, sedikitnya ada tiga dimensi penting.
Pertama, ketahanan emosional. Yaitu kemampuan mengelola perasaan dalam situasi apa pun, baik saat berada di bawah tekanan, konflik, maupun krisis.
Individu yang matang secara emosional tidak mudah tersulut provokasi, tidak gampang putus asa, dan memiliki kapasitas untuk bangkit kembali setelah jatuh. Inilah yang dalam literatur sering disebut sebagai resiliensi (Masten, 2014).
Kedua, ketahanan sosial: kemampuan membangun relasi yang sehat dan saling percaya dengan orang lain.
Di sinilah nilai gotong royong, empati, dan solidaritas bekerja sebagai modal psikososial bangsa.
Modal sosial yang kuat terbukti menurunkan potensi konflik dan mempercepat pemulihan saat terjadi bencana atau krisis (Putnam, 2000).
Lanskap seperti ini tak bisa dikesampingkan karena terkait daya tahan warga negara kita.
Ketahanan individu bangsa kita harus teruji di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini.
Ada satu dimensi yang sering luput, padahal itu menjadi penentu bagi sebuah bangsa agar terus tegak berdiri, atau justru runtuh dari dalam, yaitu kesehatan mental warga negaranya.
Ketahanan nasional yang kokoh harus berakar pada ketahanan pribadi. Di sini, sedikitnya ada tiga dimensi penting.
Pertama, ketahanan emosional. Yaitu kemampuan mengelola perasaan dalam situasi apa pun, baik saat berada di bawah tekanan, konflik, maupun krisis.
Individu yang matang secara emosional tidak mudah tersulut provokasi, tidak gampang putus asa, dan memiliki kapasitas untuk bangkit kembali setelah jatuh.
Inilah yang dalam literatur sering disebut sebagai resiliensi (Masten, 2014).
Kedua, ketahanan sosial: kemampuan membangun relasi yang sehat dan saling percaya dengan orang lain.
Di sinilah nilai gotong royong, empati, dan solidaritas bekerja sebagai modal psikososial bangsa.
Modal sosial yang kuat terbukti menurunkan potensi konflik dan mempercepat pemulihan saat terjadi bencana atau krisis (Putnam, 2000).
Ketiga, ketahanan moral dan ideologis: kemampuan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan jati diri bangsa di tengah arus ideologi transnasional, konsumerisme, dan hedonisme digital.
Individu yang sehat mentalnya akan lebih mampu memilah informasi, menjaga integritas, dan tidak mudah terseret pada paham radikal dan destruktif.
Pertanyaannya, kemudian, bagaimana menjadikan kesehatan mental sebagai agenda strategis negara, bukan sekadar kegiatan seremonial atau program proyek jangka pendek?
Pertama, pendidikan kesehatan mental sejak dini perlu menjadi bagian integral kurikulum. Anak-anak dan remaja tidak hanya belajar berhitung dan menghafal, tetapi juga dilatih mengelola emosi, mengembangkan empati, menyelesaikan konflik, dan mengenali kapan mereka membutuhkan bantuan.
Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan manusia seutuhnya (Bronfenbrenner, 1979). Kedua, kita harus mengikis stigma.
Di banyak keluarga, mengaku lelah secara mental masih dianggap kelemahan Iman atau kurang syukur.
Di sekolah dan tempat kerja, datang ke psikolog kadang dipandang sebagai tanda “tidak normal”. Padahal, mencari bantuan justru tanda kedewasaan.
Budaya terbuka terhadap isu kesehatan mental perlu dibangun di rumah, sekolah, kampus, kantor, hingga ruang publik.
Ketiga, kapasitas profesional perlu diperkuat, tetapi pendekatan berbasis komunitas tidak boleh dilupakan.
Tenaga psikolog, psikiater, konselor sekolah, pekerja sosial, penyuluh agama, hingga tokoh adat perlu bergerak bersama sebagai jaringan pendukung kesehatan jiwa di tingkat paling dekat dengan warga.
Keempat, kita memerlukan kebijakan nasional yang mengarusutamakan kesehatan mental ke seluruh sektor pembangunan —pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, transportasi, hingga keamanan.
Kesehatan mental tidak bisa hanya dibebankan pada satu kementerian. Ia harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang.
Kelima, kita mesti menggali kembali nilai-nilai resiliensi khas Indonesia: gotong royong, kekeluargaan, kesederhanaan, dan religiusitas yang menenteramkan.
Nilai-nilai ini perlu diterjemahkan ke dalam program-program nyata, bukan hanya slogan.
Di banyak daerah, kearifan lokal terbukti efektif menjadi penyangga kesehatan mental masyarakat dalam situasi krisis (Koentjaraningrat, 2009).
Keenam, ketahanan digital harus menjadi prioritas baru.
Tantangan kesehatan mental generasi muda hari ini banyak lahir dari layar gawai: perbandingan sosial di media sosial, cyberbullying, hoaks, hingga adiksi gim dan konten instan.
Pendidikan literasi digital yang memuat aspek psikologis dan etika tak bisa ditunda (Livingstone & Helsper, 2019).
Pengaturan yang bijak atas akses media sosial bagi anak juga menjadi bagian dari perlindungan generasi masa depan.
Melalui langkah-langkah tersebut, kita sedang membangun bukan hanya sistem layanan kesehatan mental, tetapi juga ekosistem yang membuat setiap warga merasa diakui, didengar, dan didampingi.
Itulah fondasi ketahanan nasional yang sesungguhnya.